Pekalongan Darurat Ekologis: Banjir Kota, Longsor Pegunungan, dan Krisis Tata Ruang
SANTAIREKOMENDASI
Kiri Kanan Atas Bawah
6/16/20253 min baca
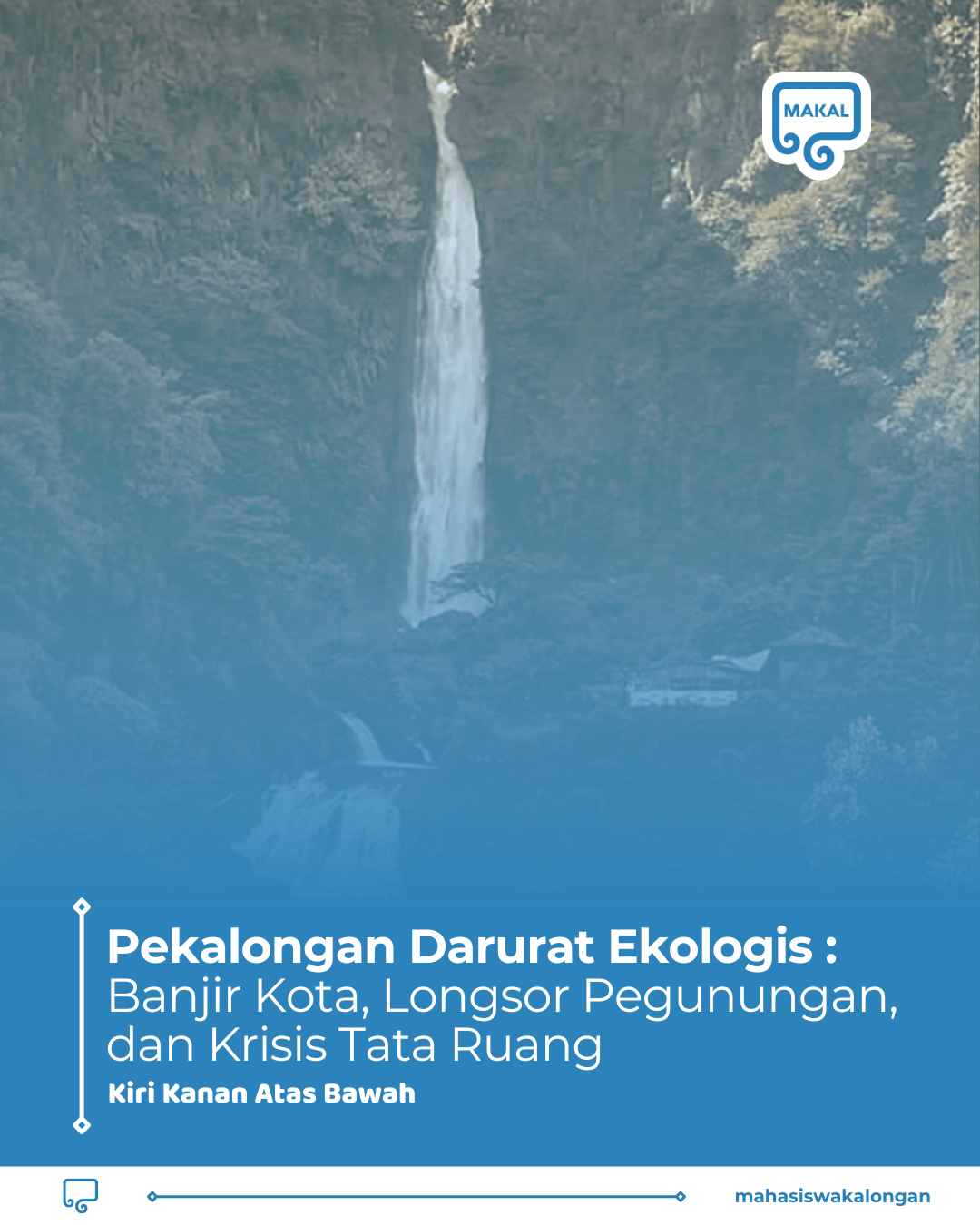
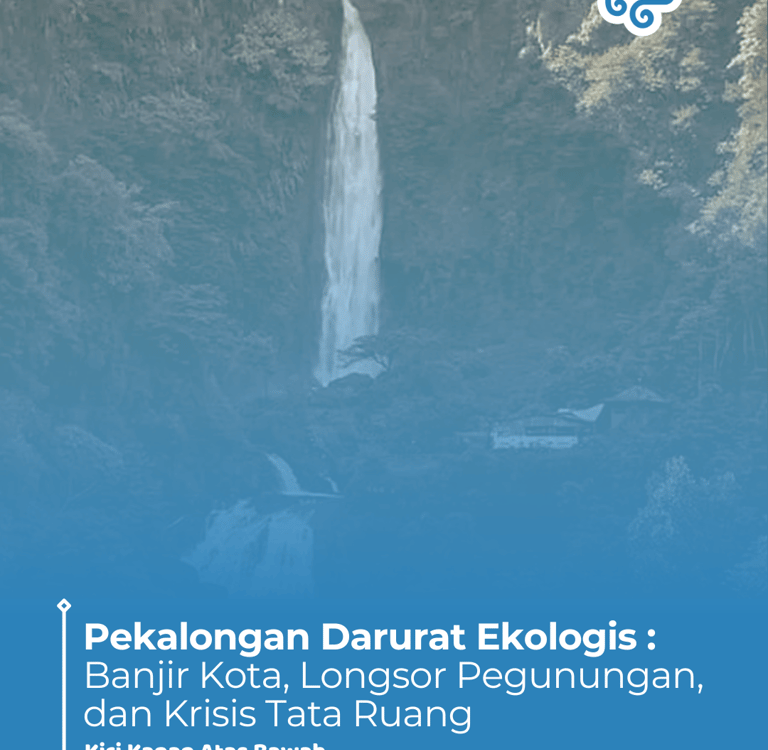
Pekalongan, sebuah kota dan kabupaten yang dikenal akan kekayaan budaya batiknya, kini berada di tengah kondisi darurat yang jarang dibicarakan secara serius: darurat ekologis. Dalam beberapa tahun terakhir, bencana alam yang dahulu hanya bersifat musiman kini berubah menjadi kejadian yang makin rutin dan mengkhawatirkan. Banjir hampir setiap tahun melanda wilayah kota dan pesisir, sementara tanah longsor kerap terjadi di kawasan pegunungan seperti Petungkriyono, yang notabene merupakan paru-paru hijau Pekalongan. Fenomena ini bukan semata-mata gejala alamiah, melainkan akibat dari krisis ekologis yang dipicu oleh kerusakan tata ruang dan eksploitasi alam secara berlebihan.
Banjir Kota: Air yang Tak Lagi Terserap Tanah
Di wilayah kota dan pesisir seperti Tirto, Poncol, maupun daerah sekitar aliran Sungai Loji, banjir telah menjadi rutinitas tahunan, bahkan bulanan. Genangan air tidak lagi hanya terjadi saat musim hujan ekstrem, tetapi juga ketika hujan sedang atau bahkan pasang laut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem drainase sudah tidak mampu mengimbangi limpahan air, dan daya serap tanah yang terganggu akibat pembetonan masif menjadi faktor utama. Pembangunan perumahan, jalan, dan kawasan komersial tanpa memperhatikan fungsi resapan tanah mempercepat pergerakan air hujan menjadi limpasan permukaan.
Lebih dari itu, pengabaian terhadap kawasan hijau dan ruang terbuka menjadikan kota kehilangan kemampuannya untuk menahan air. Alih fungsi lahan dari sawah dan rawa menjadi permukiman dan kawasan industri, tanpa penyeimbang ekologis yang memadai, menambah kompleksitas masalah ini.
Longsor di Petungkriyono: Alam Pegunungan yang Merana
Sementara banjir menggenangi dataran rendah, kawasan tinggi seperti Petungkriyono menghadapi ancaman lain yang tak kalah serius: tanah longsor. Wilayah yang selama ini dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang rimbun, kini mengalami kerentanan luar biasa karena pembukaan lahan, penebangan liar, dan pembangunan jalan yang memotong kontur tanah secara tidak bijak.
Longsor yang terjadi di Petungkriyono bukan hanya merusak akses dan permukiman, tetapi juga mengancam ekosistem pegunungan yang menjadi sumber air bersih dan penyangga iklim lokal bagi wilayah di bawahnya. Jika krisis ini tidak dikendalikan, maka tidak hanya Petungkriyono yang akan kehilangan fungsinya sebagai benteng ekologis, tetapi seluruh sistem alam Pekalongan akan terancam kolaps.
Krisis Tata Ruang dan Absennya Keadilan Ekologis
Baik banjir di kota maupun longsor di pegunungan, keduanya menunjuk pada akar persoalan yang sama: kegagalan tata ruang dan ketimpangan dalam pengelolaan lingkungan. Tata ruang yang lebih berpihak pada kepentingan ekonomi jangka pendek—seperti pembangunan properti, industri, dan infrastruktur—telah mengorbankan keseimbangan ekologis. Rakyat kecil menjadi korban: rumah mereka kebanjiran, mata pencaharian terganggu, bahkan nyawa pun melayang saat longsor menerjang.
Krisis ekologis ini bukan hanya soal kerusakan alam, tetapi juga tentang ketidakadilan struktural. Mereka yang tidak ikut merusak justru menjadi korban utama, sementara aktor-aktor besar yang mengeksploitasi sumber daya masih terus leluasa bergerak. Dalam konteks ini, darurat ekologis harus dibaca pula sebagai darurat keadilan sosial dan keadilan lingkungan.
Menuju Solusi: Restorasi Ekologis dan Kesadaran Kolektif
Mengatasi darurat ekologis di Pekalongan membutuhkan lebih dari sekadar normalisasi sungai atau pembangunan tanggul. Restorasi ekologis harus menjadi agenda utama: reboisasi di kawasan pegunungan, perlindungan kawasan resapan, moratorium alih fungsi lahan, dan revitalisasi sistem drainase kota yang berkelanjutan. Pemerintah daerah harus mulai berani melawan kepentingan ekonomi yang merusak lingkungan dan membangun tata ruang yang berpihak pada keberlanjutan ekologis.
Tak kalah penting adalah kesadaran kolektif masyarakat. Krisis ini hanya bisa diatasi jika semua pihak—pemerintah, pengusaha, warga, dan organisasi masyarakat sipil—berkolaborasi dalam satu visi yang sama: menyelamatkan Pekalongan dari kehancuran ekologis yang lebih luas.
Pekalongan tidak hanya darurat banjir atau longsor. Pekalongan sedang berada di ambang darurat ekologis. Ini bukan bencana alam semata, melainkan krisis buatan manusia. Maka solusinya juga harus datang dari keberanian manusia untuk berubah—menata ulang ruang, mengembalikan keseimbangan alam, dan menegakkan keadilan ekologis bagi semua.
Daftar Referensi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pekalongan. (2022). Laporan Tahunan Kebencanaan Kabupaten Pekalongan.
Kompas. (2023, Maret 12). Warga Pekalongan Mengungsi Akibat Banjir Berhari-hari. https://www.kompas.com
Tempo. (2021). Pekalongan Hadapi Rob dan Longsor, Pemerintah Dinilai Lambat Bertindak. https://www.tempo.co
Bappeda Kota Pekalongan. (2020). Kajian Rencana Tata Ruang dan Strategi Penanganan Banjir.
Wahyudi, E. (2020). “Penurunan Muka Tanah dan Ancaman Rob di Kota Pekalongan.” Jurnal Geografi dan Lingkungan, 12(1), 45-58.
WALHI Jawa Tengah. (2023). Krisis Ekologis di Pekalongan: Kajian Lapangan dan Rekomendasi Kebijakan.

